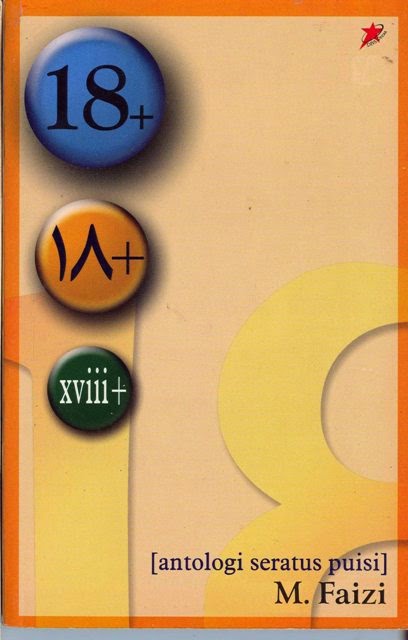Lewat tangga berjalan aku menuju kotamu. Lorong lorong
sesak.suara para combre seperti memburu kuntilanak.
Betapa bising dan misteri, kawan.
Di persimpangan hanya ada iklan iklan berebut simpati dgn
wajah kosong penuh debu. Aku menduga itu wajah yg menyaru.
Betapa kelu kotamu, kawan.
Langit penuh huru hara. Suara di luaran sana berjibaku
seperti sebuah pasien dalam raungan maut, menembus kemacetan.
Aku terperangkap dalam jelaga hitam yg berarakan, seperti
orang orang berbondongan mencari kota baru. Kota yg sering kau ceritakan biru
dan tak berdebu.
Lewat tangga berjalan ini kawan, aku lihat pintu kota
seperti gerbang tua yg menunggu purba.
2017
****
Manuskrip Kota (24) adalah puisi serial karya Rakhmat Giryadi,
seorang teatrawan yang juga sering menulis Puisi. Cak Gir—panggilan akrabnya—agaknya
memang menulis beberapa puisi bertema kota. Puisi ini adalah puisi yang nomor
24 (sebagaimana tercantum di judul. Saya menemuannya secara sepintas di kabar
berita Facebook, 24 Oktober 2018. Langsung saja saya ‘garap’ dengan pendekatan
suka-suka: #tafsirpuisimanasuka
“Manuskrip Kota (24”
Lewat tangga berjalan (eskalator, diterjemahkan menggunakan
pola frase atributif berimbuhan [yaitu satuan
bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang satu kata tersebut merupakan
unsur perluasan dari kata yang lain dan unsur perluasannya itu berimbuhan] aku
menuju kotamu (penyair mengganggap kotamu itu hanyalah semacam lantai dua atau
lantai tiga di suatu pertokoan; simbolis). Lorong lorong sesak (karena
orang-orang yang berseliweran dan sibuk. DI samping lorong yang sesak,
lorong-lorongnya juga ramai karena dipenuhi) suara para combre (entah apa combre
itu, yang pasti suaranya berisik dan menakutkan yang tergambar dalam ungkapan
penyair bahwa mereka) seperti (sedang) memburu kuntilanak.
Betapa bising (kotamu) dan (betapa ia penuh) misteri, kawan.
Di persimpangan (maksudnya di tempat yang ramai, pusat
publik) hanya ada iklan iklan berebut simpati (dari para pelalu lalang.
Iklan-iklan itu mungkin bukan papan iklan [billboard] biasa, tetapi iklan calog
legislatif karena ada penanda ke arah itu, yakni) dgn wajah kosong penuh debu
(yang meskipun wajahnya tersenyum dan mengkilat karena sudah masuk bengkel
rekayasa digital, ia masih tampak menyimpan keraguan dan kecemasan, masih
kosong. Sebab itulah). Aku menduga itu wajah yg menyaru (karena wajah sejatinya
tidaklah seperti itu).
Betapa kelu (artinya tidak bisa menyampaikan sesuatu secara
jelas, tidak jelas konsepnya) kotamu, kawan.
Langit penuh huru hara (barangkali, yang dikehendaki si
penyair adalah keberisikan bunyi mesin, klakson, knalpot, serta sumber suara
lainnya yang tidak merdu, polusi suara di antara polusi udara. Maka dari itu,
ia menyatakan kalau). Suara di luaran sana berjibaku (antara suara yang satu
dengan suara lainnya) seperti sebuah pasien dalam raungan maut (pada masa-masa
klimaktorium), menembus kemacetan (bagian ini mengacu pada baris pertama di
bait ini, bukan penjelas pada kalimat sebelumnya).
Aku terperangkap dalam jelaga hitam yg berarakan (“jelaga
hitam yang berarakan”, secara denotatif, boleh jadi sebagai gambaran asap
knalpot kendaraan bermotor bermesin disel yang belum ‘tersertifikasi’ standar
emisi gas buang EURO, tetapi secara konotatif, penyair memaksudkannya sebagai
serangkaian persoalan yang berbanjar-banjar, panjang dan mengular, yang membelit
seluruh problem kota yang dimaksud si penyair. Hal itu diibaratkannya), seperti
orang orang berbondongan mencari kota baru (tempat tinggal yang baru, yang
penuh harapan, tapi bukan Kota Harapan Indah di Bekasi. Yang dicari mereka
barangkali adalah). Kota (idaman) yg sering kau ceritakan biru (simbol
kemajuan) dan tak berdebu (maksudnya bersih).
Lewat tangga berjalan (repetisi, menegaskan situasi seperti
di muka) ini kawan, aku lihat pintu kota seperti gerbang tua yg menunggu purba
(jika pada bagian awal penyair cemas dan pesimis tentang keberadaan suatu kota,
hingga pada bagian penutup puisi, si penyair semakin meyakini kebenaran
pernyataannya sebagaimana di muka, yakni kota yang dimaksud—kota tempat tinggal
kawannya itu, mungkin Jakarta atau Bekasi—mungkin saja, lho—akan segera menjadi
kota yang ramai [sebagai ciri kota metropolitan] meskipun pada dasarnya, kerena
adanya tata kota atau tidak adanya konsep yang jelas yang menjadi identitas
kota tersebut, ia akan segera menjadi kota yang ketinggalan zaman.
2017 (artinya puisi ditulis tahun 2017, entah tangga dan
bulannya)
M. Faizi 25 Okt 2018