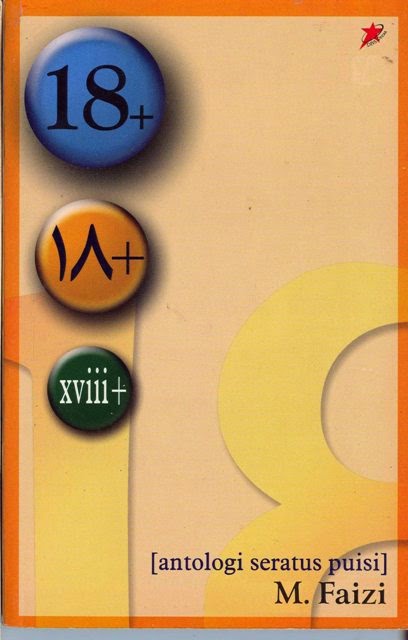Sebagian cerita maha duka dari lirih tempo alunan piano,
adalah komposisi purna menyayat perasaan kehilangan
keindahan musim semi di Vienna, bunga melayu di mataku.
Malam ini bulan tidak bulat purnama bersama sonata
bergulir bagai drama dalam partitur Una Fantasia
dengan tempo adagio, mengelus-elus pendengaran.
Imajinasiku melambung jauh ke pintu peradaban
klasik dalam concerto berirama haru, lalu melambat
seperti bunga-bunga kematian, aku disergap kesedihan.
Jarak di antara dua belas pinus di tepi danau Lucerne,
di hutan empat musim dalam melodi rumit, membawa
kaki berlari dari kejaran hari-hari tanpa jeda. Bukankah
hidup adalah detak detik bergerak, wujud setiap rencana?
Tapi segalanya memang harus berakhir ketika layar
ditutup. Aku tersadar dari sihir partitur klasik pemuja
seni yang mengembara di udara beraroma rindu.
Sebuah kisah terbakar api, tapi puisi-puisiku tetap abadi.
2017-2018
 |
| M Faizi, macak nulis di Jembatan Beethoven, Leipzig |
“Komposisi Beethoven: Moonlight Sonata”
(Puisi Weni Suryandari kali ini bertema musik klasik.
Definisi Klasik—apabila ia mengacu kepada masa tertentu—dapat diperdebatkan,
tapi ketika ia mengacu kepada sonata, lebih-lebih pada karya Moonlight
Sonata-nya Beethoven, selesai sudah masalah. Orang boleh berbeda pendapat soal
masa itu, periode itu, tetapi mereka akan sepakat bahwa “Moonlight Sonata”
[‘moonlight’ bermakna cahaya bulan; ‘sonata’ bermakna komposisi
musikal-instrumentalia) adalah satu karya maestro dan virtuoso, Ludwig van
Beethoven, seorang komponis Jerman-Austria yang sangat masyhur, atau malah yang
paling masyhur. Weni, penyair kita kali ini, berandai-andai bahwa Moonlight
Sonata merupakan) Sebagian cerita maha duka dari lirih tempo alunan piano,
(bagi penyair, komposisi ini)
adalah komposisi purna menyayat perasaan kehilangan
(akan)
keindahan musim semi di Vienna (ibu kota Austria,
lidah kita menyebutnya Wina, bukan Weni, apalagi Wine), bunga melayu di mataku
(penjelasan dari kalimat sebelumnya; perlambang kesedihan yang mendalam).
Malam ini (yakni pada malam ketika puisi ditulis atau
pada saat si penyair mendengarkan komposisi Moonlight Sonata yang membuat dia
terinspirasi untuk menulis puisi ini, kondisi) bulan tidak bulat purnama (maksudnya,
tidak benar-benar purnama, mungkin perbani, yaitu proses menjelang purnama) bersama
sonata (yang menjadi latarnya)
bergulir bagai drama dalam partitur Una Fantasia (Apa
partitur Una Fantasia? Adakah varian dalam notasi? Saya kurang tahu. Yang saya pahami,
bahwa penyair menangkap situasi dramatis di situ sehingga ia mengumpamakannya
dalam frase “bagai drama”. Maksudnya, perpindahan notasi di dalam partitur
itulah disebutnya drama, bisa terkait tempo atau birama)
dengan tempo adagio (terkait dengan birama dan jeda; istilah
untuk tempo yang lambat, bukan nama koran atau majalah. Biasanya, yang begini
ini mengesankan kemurungan atau meditatif, sehingga wajar apabila si penyair
merasakan komposisi itu dapat), mengelus-elus pendengaran.
Rupanya, penyair Weni begitu serius mendengarkan komposisi
ini. Ia semata-mata mendengarkan, tidak mendengarkan sambil lalu, seperti
mendengarkan sekaligus sambil bersih-bersih kamar atau memasak. Pantas saja,
komposisi tersebut—menurut pengakuannya—membuat) Imajinasiku melambung jauh
ke pintu peradaban
klasik (“peradaban klasik” yang dimaksudkan penyair
boleh jadi Abad Pencerahan, tetapi jika menilik redaksi puisi, yang dimaksudkannya
agaknya adalah masa-masa abad 16 hingga abad 17-an, yakni masa di mana
komposer-komposer musik klasik lahir dan berjaya) dalam concerto berirama
haru, lalu melambat (soal ketukan; tempo, yang membuat suasana batin
pendengarnya pun berubah. Penyair menangkap kesan kesedihan yang mendalam)
seperti bunga-bunga kematian, (sehingga) aku disergap
kesedihan.
Jarak di antara dua belas pinus di tepi danau Lucerne
(nama danau indah di Swiss),
di hutan empat musim (maksudnya bukan hutan tropis) dalam
melodi rumit (seperti di dalam komposisi, mengesankan sebuah upaya yang
rumit di antara nuansa tenang yang tercipta dari sonata. Komposisi itu tak
ubahnya kekuatan yang), membawa
kaki berlari dari kejaran hari-hari tanpa jeda (Sebentar,
mengapa penyair, kok, tiba-tiba berfantasi terhadap barisan pohon pinus di
danau Lucerne? Kemungkinan yang pertama, Moonlight Sonata berasosiasi dengan
tempat itu; kemungkinan kedua, penyair bernostalgia dengan tempat tersebut
ketika puisi ini ditulis; kemungkinan yang ketiga, penyair sedang membandingkan
komposisi klasik ini dengan tempat yang tenang dan sama indahnya dengan citraan
yang berbeda indera, semacam sinestesia. Setelah menggambarkan suasana yang
berbeda ini, penyair lantas mengajukan pertanyaan retoris:). Bukankah
hidup adalah detak detik bergerak, wujud setiap rencana?
Namun, segala yang ia rasakan, baik itu kesedihan atau
kebahagiaan, akan mengalami masanya sendiri. Yang pernah bermula akan pula
berakhir. Katanya:)
Tapi segalanya memang harus berakhir ketika layar
ditutup (dan ungkapan ini agaknya merupakan gambaran
bagian akhir komposisi Moonlight Sonata, menjelang selesai). Aku tersadar
dari sihir partitur klasik pemuja
seni yang mengembara di udara beraroma rindu (bagian
ini menunjukkan bahwa si penyair—yang dalam hal ini merupakan pendengar
sekaligus penikmat karya-karya musik klasik—sempat terhanyut oleh alunan musik,
laksana seorang ‘astral traveler’, melintasi abad demi abad tetapi tetap dalam
keadaan tidak berpindah tempat duduk. Demikian pula, komposisi tersebut dapat
membawanya melambung jauh ke masa/periode Klasik tetapi tetap dalam keadaan terpekur
di depan laptop. Baginya, keadaan ini bagaikan)
Sebuah kisah terbakar api (dan karenanya menjadi
musnah. Lalu, apa yang tersisa? Meskipun yang lain akan musnah), tapi
puisi-puisiku tetap abadi.
2017-2018
@ M Faizi
@ M Faizi